
”Masih jauh?” tanya Badrun tanpa menoleh. Kedua tangannya memeluk tas ransel yang ada di pangkuannya. Kaki kirinya terus bergoyang-goyang tanpa bergeser sedikit pun posisinya.
”Paling setengah jam lagi,” jawab Rozi sambil menggeser kepalanya mendekati jendela yang terbuka. Ia selonjorkan kursinya ke ruang kosong yang ada di depan jok yang didudukinya.
”Tadi jadi nelepon istrimu?”
”Jadi,” jawab Badrun lagi-lagi tanpa menoleh dan tanpa menggeser tangan dan kakinya sedikit pun. Jawabannya pendek dan terasa enggan. Membuat Rozi salah tingkah dan memilih diam.
Mobil Colt tanpa AC itu terasa kian pengap. Sopir mengeraskan musik dangdut yang sedang ia putar sambil ikut menyanyi dengan suara keras tak peduli ada dua orang penumpang di belakangnya.
”Kamu nggak mau nelepon siapa-siapa?” tanya Badrun kali ini sambil menoleh ke arah Rozi.
”Mau nelepon siapa?” Rozi malah bertanya balik sambil tertawa. ”Nggak punya istri!”
”Ya ibumu tho,” jawab Badrun sambil menatap Rozi. Kaki kirinya masih terus bergoyang.
”Ibuku sudah tua. Sudah pikun. Jangan-jangan juga sudah lupa punya anak bungsu yang namanya Rozi. Saking banyaknya anaknya yang lain,” jawab Rozi sambil terkekeh.
”Memang punya berapa saudara?”
”Tujuh! Aku yang kedelapan. Cuma sisa-sisa ampas. Nggak pernah diurusin juga bisa besar sendiri. Aku hilang juga tidak ada yang nyari. Aku mati juga paling tak ada yang nangisi.” Rozi masih terkekeh. Badrun meliriknya dengan heran.
”Tapi tak lama lagi aku pasti bisa kumpul sama Mamak. Berdua saja. Biar kumanjakan dia dengan apa saja yang ia minta. Biar sadar dia kalau hanya aku yang bisa bikin dia bahagia,” lanjut Rozi. Kata-katanya penuh penekanan. Terlihat ia sangat yakin dengan apa yang sedang ia katakan.
”Kumpul di mana?” Badrun bertanya pelan penuh rasa heran.
”Di surgalah! Di mana lagi? Mamak sudah sangat tua. Paling tak sampai setahun ia sudah menyusulku ke sana.”
Badrun menelan ludahnya. Goyangan kakinya semakin keras. Ia peluk ranselnya semakin erat.
”Istri dan anakku masih lama nyusulnya,” kata Badrun pelan. Lebih menyerupai bisikan pada dirinya sendiri. Tapi Rozi masih bisa mendengarnya.
”Ya bagus. Bisa lebih lama mendoakan kamu. Doa anak untuk bapaknya katanya doa paling manjur.”
”Lha apa orang seperti kita ini juga masih butuh doa?”
”Hehhehheh,” Rozi memainkan suara tawanya. Ia tak menjawab pertanyaan Badrun dan malah memilih untuk mengalihkan pandangannya ke luar jendela.
Mereka berdua diam. Suara sopir yang sedang menyanyi mengikuti lagu yang sedang diputar terdengar semakin jelas.
”Memang bidadarinya secantik apa tho, Zi?” Badrun membuka mulutnya tanpa menoleh ke Rozi.
”Heh?” Kini suara ”heh” dari mulut Rozi bukan lagi suara tawa yang dibuat-buat, melainkan letupan kaget atas pertanyaan Badrun.
”Aku nanya, bidadarinya secantik apa?” Badrun mengulang pertanyaannya lagi-lagi tanpa menengok ke arah Rozi.
”Katanya sih, cuantiiiik banget. Kecantikan yang tak bisa dibayangkan oleh akal kita,” jawab Rozi dengan kalem. Ia tak lagi bicara sambil tertawa atau cengengesan. Matanya beberapa saat dipejamkan, seperti sedang mencari-cari bayangan kecantikan itu dalam kegelapan penglihatannya.
”Kayak Desy Ratnasari?” Badrun kini bertanya sambil memandang Rozi.
”Walah, kalau itu ya jelas lewat jauh!” jawab Rozi sambil memainkan tangannya, seolah ingin memberikan penekanan pada kata lewat jauh yang diucapkannya. ”Agak kearab-araban barangkali ya. Yang matanya lebar, hidung bangir, kulit putih. Aaahh!”
Keduanya mengikik. Seperti sedang menertawakan diri mereka sendiri.
”Kamu sudah pernah kawin, Zi?”
”Sudah dibilang enggak punya istri.”
”Iya, kawin kan enggak perlu punya istri.”
Mereka tertawa kecil bersama.
”Belum pernah, Drun. Enggak ada yang mau sama aku,” jawab Rozi masih sambil tertawa.
Badrun tertawa kecil. ”Pantas kamu sudah mau cepat-cepat ketemu bidadari.”
”Kalau itu betul. Siapa yang tak mau ketemu bidadari!”
Lagi-lagi mereka mengikik bersama. Tawa yang begitu lirih dan tertahan, yang lebih menyerupai suara isakan dibanding suara tawa itu sendiri.
”Nanti akan sesakit apa ya, Zi?”
”Ah, kau ini Drun! Sudah hampir sampai masih pula tanya akan sesakit apa.”
”Sebenarnya aku ini penakut, Zi.”
”Sudah pastilah kita yang memilih jalan ini penakut, Drun. Takut dosa. Takut sama Allah. Juga takut sama hidup.”
”Sudah sempat makan kau tadi, Drun?”
Badrun menggeleng. ”Enggak ada selera. Lapar pun sudah tak terasa.”
”Jangan begitu. Makanan enak mungkin hanya satu-satunya yang layak kita kenang dari dunia yang jahanam ini,” kata Rozi sambil merogoh tas yang ada di samping kakinya. ”Nasi padang!”
”Ini,” katanya sambil menyerahkan satu bungkus pada Rozi. ”Aku tadi beli dua bungkus. Sama-sama pakai rendang, limpa, otak. Pokoknya kita harus makan enak. Biar kita makin bersyukur dan bisa menuntaskan perjuangan kita ini.”
Badrun menerima sebungkus nasi yang diberikan Rozi, tapi ia tak juga membukanya. Rozi tak peduli. Ia makan nasi itu dengan tangannya, begitu lahap seolah tak ada kerisauan sedikit pun di dalam hatinya.
”Di sana nanti enggak ada nasi padang, Zi,” kata Badrun sambil tertawa.
”Kata siapa?” tanya Rozi dengan mulut penuh nasi. ”Apa pun bisa kita dapatkan di sana. Nasi padang, sate kambing, ayam goreng, pizza, semua tinggal tunjuk saja! Gratis!”
”Minum bir boleh enggak di sana?”
”Huahahahaha…!” Rozi tak menjawab selain dengan tawa yang terbahak-bahak. Badrun membalasnya dengan ikut tertawa walaupun dalam hatinya ia benar-benar ingin tahu apakah di tempat yang sedang mereka tuju akan disediakan bir atau tidak.
”Mudah-mudahan tubuhku nanti tetap utuh ya, Zi,” kata Badrun sambil mengusap mukanya.
”Apa bedanya?” tanya Rozi sambil menjulurkan tangannya ke luar jendela, mencucinya dengan air minum dalam botol.
”Ya biar bisa dilihat sama anak istriku.”
”Huahahahahaha…!” Rozi terbahak-bahak. Sangat keras hingga membuat sopir menengok ke belakang. Rozi melambaikan tangannya pada sopir dan berkata, ”Lanjut dangdut!” Sopir itu tersenyum dan kembali lagi sibuk dengan musik yang sedang diputarnya.
”Kok malah tertawa?”
”Ya kamu itu goblok! Harusnya kamu berharap agar tubuh kita itu hancur sehancur-hancurnya. Biar tak ada lagi yang bisa mengenali. Biar tidak ketahuan kita siapa.”
”Aku masih ingin bisa pulang ke anak istriku, Zi. Dimakamkan di dekat mereka.”
”Kamu yakin istrimu masih mau nerima?” kata Rozi dengan nada mengejek. Badrun tak menjawab apa-apa.
”Memang kamu tadi bilang apa ke istrimu?”
”Enggak bilang apa-apa.” Badrun menjawab dengan enggan. Rozi pun memilih diam.
”Sudah hampir sampai,” kata Rozi kemudian sambil melirik jam tangannya.
”Mall-nya ada di depan itu,” kata sopir tanpa menolehkan kepalanya ke belakang. ”Nanti saya turunkan di depan lobi lalu langsung saya tinggal. Ada penumpang lain yang nunggu.”
Rozi mengambil tas yang menyandar di kakinya, memangkunya dan memeluknya sebagaimana yang sejak tadi dilakukan Badrun. Badrun memejamkan matanya. Kaki kirinya masih terus bergoyang, bahkan kini kian keras.
”Bidadarinya nanti langsung jemput kita, Zi?” Badrun bertanya lirih, nyaris berbisik, tanpa membuka matanya.
”Katanya begitu,” jawab Rozi juga dengan lirih.
Mobil berhenti. Musik dangdut masih terus mengalun, tapi sopir itu tak lagi ikut menyanyi. Rozi membuka pintu di sampingnya sambil mengangkat ransel yang dipangkunya. Badrun mengikutinya. Mobil langsung bergerak saat Badrun menutup pintu yang dilewatinya.
Mereka berjalan bersama menuju pintu kaca yang dilewati banyak orang dengan memanggul tas ransel di masing-masing punggung mereka.
”Nanti bidadari yang jemput satu atau dua, Zi?” bisik Badrun tepat di telinga Rozi.
”Sepuluh, Drun,” bisik Rozi. ”Sepuluh bidadari akan menjemput kita.”
(Sumber: harian Kompas edisi 14 Februari 2016, halaman 27 dengan judul "Dua Pengantin." oleh okky madasari)
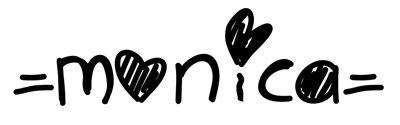








0 komentar:
Post a Comment